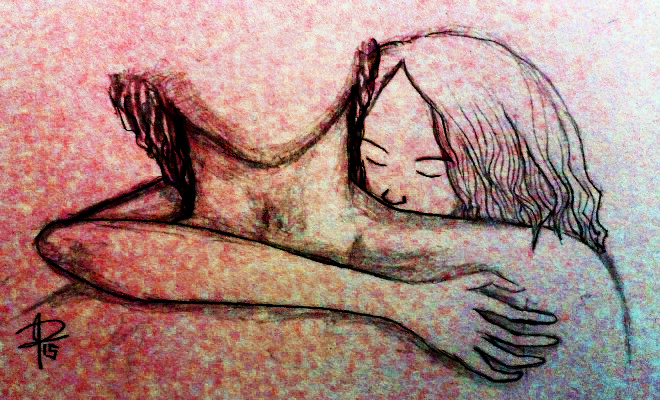Tidak hanya tubuh perempuan itu, bibir serta hidungnya pun mungil dan lagi menggemaskan. Jika bibir itu kemudian berganti senyum, tak ada laki-laki yang tak segera jatuh hati dan menaruh harap padanya. Mereka tak akan sanggup menghindar dari tatapan perempuan itu. Sebab di matanya terbentang laut, dan ketika ia memejamkan mata, badai dan gempa bumi seolah terjadi lewat cara yang tidak biasa. Aku pernah mengalami badai dan gempa bumi bersama perempuan itu. Matanya benar-benar biru. Rambutnya lebih indah dari model ternama, bahkan melebihi bintang iklan shampoo. Kukira ibu ingin aku menikahi perempuan itu.
Aku lihat Wina sedang asyik mengamati buku-buku yang sedikit terserak di dekat tempat tidurku. Ia tampak lebih riang dari beberapa hari lalu ketika badai dan gempa bumi bisa terjadi kapan saja, sekehendakku malah. Lain lagi ketika aku masih cukup waras untuk tidak menyentuhnya. Aku bahagia dengan keputusanku malam itu. Barangkali ibuku juga merasakan hal yang sama.
Perempuan itu membuatku segera jatuh hati meski dengan mendengar ceritanya saja.
Ia tidak benar-benar mengharapkan berada di rumah pelacuran, kecuali untuk dua hal. Pertama, bapak dan ibunya meminjam uang kepada pemilik salah satu rumah pelacuran. Niat awal mereka, yaitu ingin menggarap lagi sawah mereka di kampung halaman. Kedua, cita-cita itu ikhlas mereka lupakan karena Wina diterima di sekolah kedokteran.
Meski bapak dan ibunya pernah merasakan pendidikan di sekolah modern, mereka tahu persis bahwa tidak sembarang orang dapat menimba ilmu di sekolah tinggi kedokteran. Itu seperti sekolah tinggi khusus, dan mereka pun paham, bahwa biaya sekolah tinggi Wina jauh lebih penting daripada impian untuk dapat menggarap lagi sawah di kampung halaman. Nyatanya, perempuan itu harus mengembalikan uang yang dipinjam bapak dan ibunya. Ia belum lagi menamatkan sekolah tinggi, sedang orang tuanya terlanjur berutang kepada pemilik salah satu rumah pelacuran. Kalaupun ada harta yang mereka miliki, maka satu-satunya harta berharga yang dimiliki bapak dan ibu Wina tidak lain adalah dirinya sendiri. Jadilah ia mengganti uang itu dengan cinta seorang anak kepada kedua orang tua, atau sebut saja harga diri seorang anak perawan.
“Kalau kamu tertarik membaca buku itu, kamu boleh menyimpannya sebagai milikmu.” Suaraku yang muncul tiba-tiba sedikit mengagetkan Wina. Matanya melekat pada sebuah buku di genggaman tangannya.
“Kamu sudah membaca buku ini, Mas?” tanya Wina, setelah melirik ke arahku yang masih terkapar malas di atas tempat tidur.
“Buku itu sudah kubaca beberapa kali. Bacalah untuk kesembuhan dirimu, mungkin juga untukku.”
Perempuan itu seperti tak peduli pada jawaban yang baru diterimanya. Entah apakah Wina tak mendengar suaraku, atau diksi ‘untuk kesembuhan dirimu’ yang keluar dari mulutku yang asam mengejek statusnya sebagai bekas mahasiswa di sekolah tinggi kedokteran. Tapi melihat Wina yang memperlakukan buku itu seperti menggendong anak bayi—tak peduli bayi itu anaknya atau bukan—aku tahu perempuan itu ingin sekali membuka halaman pertama Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur!.
Kutemukan buku itu di sebelah buku Das Capital, berada satu rak dan terselip di antara buku-buku komunis yang dijual seorang pedagang buku bekas. Aku cukup kecewa mengetahui bahwa buku yang kubeli itu tidak asli, melainkan fotokopian. Banyak buku bernasib sama dijual di pasar buku bekas di Senen. Toko buku besar di Matraman malah lebih memilih menjual alat-alat elektronik tinimbang memberikan alternatif bacaan untuk anak-anak muda yang tak begitu paham sejarah bangsanya. Atau anak-anak muda itu cukuplah belajar menjadi orang tua modern, tentu setelah toko buku besar itu nantinya juga menjual perabot rumah tangga dan perkakas tukang. Panjang umur pembodohan!
“Coba kamu buka halaman 95,” kataku kepada Wina. Ia segera mengikuti. “Maukah kamu membacakannya untukku, dari halaman itu sampai halaman 102?”
Kalau saja ibu bersamaku saat ini, ia pasti juga mau mendengar perempuan itu membacakan barang delapan halaman untuk kami. Ibu tentu akan senang jika Wina berhasil membuat orang lain terhibur, sekalipun ia bukan pelacur atau pembaca cerita yang baik.
“Ketika nalar dan imanku disiakan,” katanya.
Aku terkejut mendengar suara Wina. Seakan-akan ada penegasan pada kata “nalar” dan “imanku”, juga penegasan pada kata terakhir “disiakan”. Seakan ada perasaan kecewa, dan ia berusaha membacakan judul bab di buku karya Muhidin M. Dahlan itu dengan luka yang kembali menganga lebar. Seakan ada sesuatu yang memukul dadaku, sesak menghimpit namun aku masih bisa bernapas. Aku ingin melindungi perempuan itu. Meski nyawa adalah taruhan dan mati di pelukannya adalah hal terindah yang dapat kupersembahkan untuk ibuku.
***
“Mas. Kenapa waktu itu kamu mau menolongku?” tanya Wina, dua malam setelah ia berhasil menamatkan cerita tentang gadis berkerudung yang kecewa dengan sekumpulan orang munafik di sekitarnya, lantas ingin menjadi pelacur.
“Menurutmu, kenapa?” tanyaku, sedikit bercanda.
“Mas, plis! Aku serius! Kenapa kamu mau menolong orang yang sama sekali enggak kamu kenal?”
Aku tak dapat menjawab pertanyaan perempuan itu. Aku merasa ia masih belum siap sekadar mengenal ibuku. Mungkin sebentar lagi. Maka kukatakan padanya, bahwa aku juga pernah terlibat hubungan aneh dengan beberapa perempuan lain.
“Jadi Mas juga menolong mereka? Kok ya tuhan sampai menciptakan laki-laki tolol macam kamu, Mas? Heran aku.”
“Hahaha. Mungkin karena alasan itulah, tuhan juga menciptakan kamu. Misal malam itu yang kutemui bukanlah kamu, melainkan perempuan lain. Atau yang jadi tamu di kamarmu ternyata seorang bocah SMA, tentu lain lagi ceritanya.”
Tak kusangka Wina berpikir bahwa aku ini laki-laki tolol. Mungkin ia pernah begitu mencintai seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu meninggalkannya karena ada perempuan lain yang jauh lebih cantik dari dirinya, yang ketika berciuman tak lagi jadi ancaman menakutkan dan berpegangan tangan adalah hal yang lazim dilakukan seorang pacar. Mungkin Wina pernah begitu mencintai seorang laki-laki. Tapi perempuan itu sadar bahwa ia lebih sayang keluarganya, hingga hubungan itu terpaksa mereka akhiri dengan Wina yang mengurung di kamar kosnya dan menangis selama beberapa malam. Mungkin benar kata perempuan itu, bahwa aku kurang cerdas dalam memahami beberapa peristiwa. Terlalu percaya diri hingga mudah jatuh cinta, misalnya.
“Mas,” ucap Wina pelan.
“Ya,” kataku.
“Aku melihat beberapa coretan di dinding kamarmu. Semua kalimatnya sama. Tertulis, ibu ingin aku menikahi perempuan itu. Bahkan sejak pertama aku datang ke sini, aku enggak pernah lihat ibumu. Atau ia tinggal di tempat lain?”
“Nanti sore kuajak kamu jalan-jalan. Siapa tahu kita ketemu ibuku.”
Wina tidak berkata apa-apa lagi. Siang itu kami lalui bersama sunyi seisi ruangan. Tidak ada badai dan gempa bumi di kamarku. Sekali pun aku menghendaki badai dan gempa itu terjadi, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak berani menyentuh Wina. Ibuku akan kecewa jika aku menyentuhnya tanpa ia mencintaiku. Jadi bersama sunyi seisi ruangan, antara kami hanya sibuk membaca buku sampai menjelang sore.
***
Langit telah hampir gelap ketika kami memasuki pemakaman umum. Dua orang berjalan-jalan di pemakaman umum selayak sepasang kekasih bervakansi ke kampung halaman. Sementara laki-laki itu memanggil-manggil ibunya setiba mereka di depan rumah, perempuan yang berdiri di sebelah laki-laki itu tampak cemas dan takut. Dua orang itu aku dan Wina.
Kuajak ia bersimpuh di kuburan ibuku. Maka berdua kami tertunduk sebentar, dan tak kusadari pipiku yang tadinya kering mulai basah oleh air mata. Aku genggam tangan Wina, ia tidak menolak. Kuharap Wina mengerti kenapa aku ingin menolongnya. Sebab aku tak ingin ia bernasib sama seperti ibuku.
Ibuku mantan pelacur. Menurut pengakuan ibu asuhku yang tidak lain adalah pemilik rumah pelacuran—tempat aku pertama kali bertemu Wina—ibu sempat ingin membunuhku ketika aku masih berbentuk janin. Tapi usahanya itu gagal. Ibuku lantas menyesal karena pernah berniat membunuh anaknya yang belum lagi bisa berkata “Ibu”. Setidaknya, ia sudah tidak lagi menjadi pelacur setelah melahirkanku. Sebab kelahiranku disaksikan langsung oleh malaikat pencatat amal baik. Betapa baik malaikat itu, sampai hari kelahiranku bertepatan dengan hari kematian ibuku.
Azan magrib baru saja lewat. Aku masih bersimpuh bersama seorang perempuan dengan kerudung berwarna putih dan matanya benar-benar biru. Aku ikhlas jika tidak ditakdirkan berjodoh dengannya. Aku ikhlas jika usahaku dalam mengakhiri masa lajang di umur 30 ini kembali menuai kegagalan. Atau, aku harus bersetia pada kesunyian dan buku-buku yang kubaca. Demi ibuku yang mati usai melahirkanku, aku lebih ingin menjadi penulis daripada gigolo.
Aku bahkan tidak benar-benar yakin apakah ibu ingin aku menikahi perempuan itu. Tapi aku tetap berusaha. Sambil menggengam tangan Wina, kukatakan pada ibu bahwa kami akan segera menikah.
Jakarta, 26 Oktober 2016
Penulis: Tri Em, tinggal di Jakarta, menyibukkan diri di jombloo.co dan dapat disapa via twitter @triem_