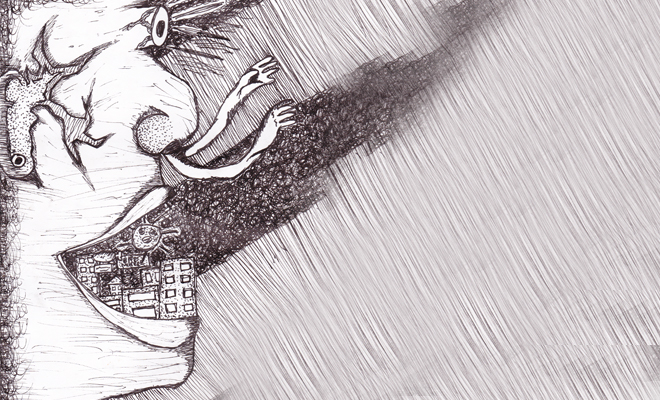“Tidak ada sejarah yang betul-betul objektif”
(George Junus Aditjondro)
Ketika pertama kali saya membaca halaman depan buku dengan judul asli “De Cheribonsche Onlusten van 1818, Naar Oorpronkelijke Stukken”. Catatan asli Van der Kemp yang telah diterjemahkan oleh B.Panjaitan. Bayangan awal yang muncul ialah saya akan membaca sebuah buku sejarah yang tersebar titik atau koma lebih dari satu di setiap kalimatnya. Sebagaimana yang selama ini saya ketahui dalam setiap buku terjemahan. Namun ketika mencoba untuk membaca, jujur saya sangat sulit dalam memahami buku ini di setiap kalimatnya. Mungkin karena bahasa asli buku ini adalah Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ditambah lagi alpanya titik atau koma yang telah saya bayangkan sebelumnya itu ternyata sama sekali tidak bekerjasama dengan pembaca demi kemudahan memahami buku ini. Alhasil setiap kalimat akan terasa panjang dan menguras nafas.
Sejarah pemberontakan petani Cirebon yang ditulis Van der Kemp ini diterbitkan oleh YAYASAN IDAYU tahun 1979. Berawal dari penerapan sistem liberal oleh Pemerintah Belanda. Van der Kemp mengatakan pada tahun 1816 markas “Kaum perusuh” berada di Krawang, namun ditengarai jika perlawanan yang sebenarnya berasal dari Cirebon. Keputusan pemerintah tanggal 8 Desember 1816 No.41 memerintahkan kepada Residen Cirebon, agar mewaspadai dan mencari tau latar belakang perpindahan Jabin, yang bersama 20 orang anak buahnya berpindah dari Laummalang ke Cirebon. Pada 6 Desember pemerintah kolonial berniat memperketat keamanan militer yang keras. Hal tersebut karena laporan residen yang menyatakan bahwa kerusuhan meningkat. Namun keinginan tersebut gagal dilaksanakan karena hantaman dari Inggris berupa ejekan yang dipublikasikan beberapa media di Inggris. Akan tetapi ketika Inggris meninggalkan pulau Jawa tanggal 19 Juni 1817. Pemerintah Belanda berhasil memperkeras peraturan bagi tuan-tuan partikelir.
Pada pertengahan kedua Januari kepala distrik Blandong dibunuh oleh pemberontak yang berjumlah 100 orang. Dalam laporan Residen Bogor muncullah nama-nama baru para pemberontak, Bagus Diwongso (Serit) dan Nairem. Ketika opsiner kehutanan dikirim ke Cirebon, Praudants, dan berhasil menyelamatkan diri dari para pemberontak. Sedangkan Heyden bersama 60 orang berusaha menyerang para pemberontak dengan menunggang kuda. Namun akhirnya ia mendapat serangan di pagi hari dan terbunuh. Sedangkan kapten Joseph Gerrish merasa beruntung karena ketika ditawan oleh pemberontak ia berhasil melarikan diri.
Surat Residen Cirebon tanggal 30 Januari memberitakan pendaratan pasukan di Batavia, disamping itu mengirimkan instruksi yang penting yaitu, serangan umum ditetapkan pada tanggal 2 Februari. Namun terjadi perselisihan antara gubernur jendral dengan panglima tentara. Akibat dari perselisihan itu serangan umum yang telah direncanakan menjadi gagal. Pada 4 Februari pemberontakan dan kerusuhan di Cirebon dipadamkan oleh Letnan Borneman dan Kapten Elout. Akan tetapi hanya Kapten Elout saja yang menerima penghargaan atas jasanya. Selain itu Neirem berhasil ditangkap dan keamanan telah pulih.
Serrit mengajak tiga sultan di Cirebon agar turut serta dalam pemberontakan yang dipimpin olehnya. Mengatahui hal itu pemerintah kolonial memberi kewenangan kepada residen, untuk mengumumkan bagi siapa saja yang mampu menangkap Serrit, hidup atau mati, akan diberikan hadiah F 2.200. tanggal 8 Agustus terjadi bentrokan antara pemberontak dengan pasukan yang dipimpin Kapten Krieger. Akan tetapi Serrit, pemimpin pemberontakan mampu melarikan diri. Di luar itu, Krieger, Residen De Rider, dan sultan sepuh mengejar para pemberontak yang melarikan diri. Pada akhirnya Serrit berhasil ditangkap. Serrit dan Neirem dijatuhi hukuman mati lain halnya dengan Sapie, Lejo, Ribut yang kemudian dibuang selama tujuh tahun sembari memakai rantai. Para tahanan lainnya, 14 tahanan dikirim ke Banda, untuk bekerja seumur hidup, 7 orang ke Banyuwangi, bekerja di kebun kopi. Krieger mendapat penghargaan besar atas jasanya karena telah berhasil meredam pemberontakan di Maluku dan Cirebon.
Tidak menutup kemungkinan Sumber-sumber utama yang dipergunakan oleh Van der Kemp, ialah dari arsip negara di negeri Belanda dan di Batavia. Bisa dikatakan pula jika penulis atau peneliti mengabaikan sumber-sumber Indonesia. Bukankah sumber lokal lebih peka terhadap masalah sosial di sekitarnya? Selain itu Pemerintah Kolonial Belanda selalu ditempatkan pada domain sebagai pencerah, pendorong kemajuan, dan senantiasa melindungi kepentingan penduduk asli.
Lingkup temporal dalam buku ini adalah tahun 1818. Tahun 1818 menjadi batasan watu pada buku ini karena pada tahun inilah terjadi aksi pemberontakan petani di Cirebon. Sedangkan ruang lingkup spasial dalam buku ini jelas yakni di Cirebon, sebab kasus yang menjadi objek penelitian penulis ini terjadi di daerah tersebut. Dengan kata lain, penulisan sejarah dalam pembahasan buku ini merupakan sejarah lokal. Dengan penulisan sejarah lokal ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengertian dalam perkembangan sejarah nasional, sebab sejarah yang ada di tingkat nasional, harus bisa dimengerti dengan lebih baik apabila kita mengerti pula perkembangan sejarah di tingkat lokal. Selain itu bagi sejarawan modern, ruang lokal menjadi patokan sebagai batas yang nantinya akan mempermudah dalam mengintepretasikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
Sejarah nasional warisan kolonial
Sejarah nasional memiliki makna yang beragam. Historiografi nasional dapat berarti penulisan sejarah yang mengkrucut pada pembangunan sebuah nasion. Bisa juga dikatakan sebagai penulisan sejarah yang dapat diterapkan kepada negara atau bangsa tertentu. Dalam artian sebuah narasi sejarah yang memicu keyakinan setiap warga negara jika masa depan negara adalah milik mereka bersama. Dalam hal ini, Van der Kemp berupaya mengikat kesadaran warga negara Belanda dengan hasil penelitian berperspektif kolonialnya. Dengan adanya narasi besar ini maka akan muncul kesadaran bersama dan hasrat yang tinggi untuk melindungi negara.
Dalam penulisan sejarah berperspektif kolonial, ada sedikit perbedaan pandangan tentang kualitas moral pemerintah kolonial dengan peranan negara. Dalam buku ini misalnya, Pemerintah kolonial Belanda dinarasikan seolah pelaku utama yang mewakili pencerahan, kemajuan, dan senantiasa melindungi kepentingan penduduk asli. Dan penyempitan cerita pun dilakukan mengenai sebab pemberontakan, bagaimana para pemberontak mengorganisir massa, upaya kekerasan yang dilakukan oleh pihak kolonial, dan sebagainya. Van der Kemp sama sekali tidak menggunakan ilmu bantu sejarah dalam menjernihkan pandangan tentang keadaan sosial, ekonomi, atau politik khususnya wilayah Cirebon.
Memang setiap orang yang menentang Belanda akan diartikan sebagai pemberontak yang bar-bar, anti rust en orde, tidak tahu terimakasih dan yang sejenisnya. Sedangkan eksploitasi dan kekejaman Belanda tidak pernah ditampilkan, malah kekejaman yang ditampilkan oleh Belanda menjadi sebuah prestasi atas jasa para pejuangnya dalam memerangi kejahatan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sartono Kartodirjo, “Tulisan mengenai sejarah indonesia oleh sejarawan Belanda atau sejarawan asing, yang sering meletakkan kekuasaan kolonial sebagai kekuatan sentral dan menyeluruh dibalik pengembang kehidupan modern dalam bentuk apapun di Nusantara.”
Jika ditinjau dari sumber-sumber yang dipergunakan oleh buku ini, sebagian besar adalah laporan-laporan dan surat resmi dari pejabat-pejabat, ketetapan pemerintah, catatan harian militer, berita-berita resmi. Memang otentisitas dokumen tidak perlu diragukan. Akan tetapi dokumen-dokumen pemerintahan itu ditulis dari sudut pandang para pejabat-pejabat kolonial. Pada akhirnya antara sudut pandang dan kecemasan pemerintah kolonial kala itu dengan pemberontakan kaum tani memiliki kuantitas yang sama.
Dari hal tersebut bisa dipahami jika sifat pokok dari historiografi kolonial ialah Eropa sentris atau pun Belanda sentris. Sepanjang peristiwa adalah serentetan aktivitas bangsa Belanda, pemerintahan kolonial, aktivitas para pegawai kompeni atau orang-orang kulit putih, berbagai hal tentang kegiatan para gubernur jenderal dalam menjalankan tugasnya di tanah jajahan. Maka dari itu, bisa dikatakan buku ini adalah sebuah sejarah warisan kolonial. Kala itu kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda menempati puncak hirarki sosial, ekonomi, maupun politik. Latar belakang mengenai hal ini bisa dikatakan, apabila fokus utama pembahasan adalah bangsa Belanda, bukanlah kehidupan rakyat atau kiprah bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda.
Pengkisahan sejarah itu jelas sebagai suatu kenyataan subyektif, karena setiap orang atau setiap generasi dapat mengarahkan sudut pandangannya terhadap apa yang telah terjadi dengan berbagai interpretasi individu. Setiap penulis berhak menyelipkan opini atau pun gagasannya mengenai sebuah peristiwa. Mungkin inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara jurnalistik dan historiografi. Sebagaimana mestinya seorang jurnalis hanya bertindak sebagai pewarta. Terlepas dari itu semua jurnalis akan melanggar kode etik jurnalisme, jika mencampuradukkan opini pribadi dalam hasil reportasenya. Oleh karena itu setiap opini pribadi dalam historiografi harus memiliki berbagai penyangga ataupun penguat pendapat itu sendiri.
Sebagaimana yang dikatakan oleh George Junus Aditjondro bahwa, “Tidak ada sejarah yang betul-betul objektif.” Bisa dikatakan jika objektifitas ialah sekumpulan subjektivitas. Yang terlebih dahulu diolah dengan berbagai kritik atau pun pertimbangan yang matang. Dalam hal ini Aditjondro berupaya mengatakan jika peringkat objektifitas ditentukan oleh seberapa besar sejarawan menekan subjektivitas. Mungkin lebih tepat bila dikatakan, bahwa objektivitas setinggi-tingginya diperoleh dengan menekan subjektivitas serendah-rendahnya. []