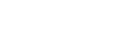Tak berjarak jauh dari ingatan kita, beberapa bulan yang lalu, Tabloid Obor Rakyat sempat menjadi bagian yang menyakiti dinamika kalangan bawah. Sebuah gaya bertutur yang dibuat provokatif, mencomot artikel di internet, dan menciptakan realitasnya sendiri. Analogi yang di gelar redaksi Obor Rakyat di halaman pertama kala itu, jurnalistik sejatinya adalah jalan pedang. Wartawan dianggap layaknya seorang tentara, keras hati, terlatih, selalu siap menerima perintah untuk membantai musuh. Jurnalisme bukanlah kritik membabi buta tanpa pondasi data dan fakta seperti itu.
Saya tidak sepakat dengan analogi tersebut. Ada banyak varian dari kritik. Salah satunya lewat jalur kesusastraan seperti Seno Gumira Ajidarma. Setelah dia didepak dari Redaksi Jakarta Jakarta karena memuat liputan mengenai pembantaian di Dili, 12 November 1991. Pada akhirnya dia memilih menyampaikan fenomena sosial yang dia tangkap melalui karya sastra. Ketika jurnalisme dibungkam, maka sastra harus bicara. Sastra merupakan jalan yang tak kasat mata bagi rezim orde baru kala itu. Sebuah karya yang tidak sembarangan, dia menyelipkan renik fakta seputar pembantaian sipil dalam kisah percintaan remaja dan filosofi jazz. Dalam hal ini ada satu hal yang bisa pelajari, upaya mengkritik pararel dengan keberanian untuk bertanggung jawab. Terlebih menyampaikan kebenaran adalah beban yang harus dituntaskan.
Agaknya tak benar jika menganggap kerja jurnalistik kami begitu sempurna. Saya pernah terlibat dalam ruang kecil hampa udara yang kami sebut LPMS Ideas. Kala kami memproses konten Majalah Ideas edisi ‘Malapetaka Pasar Tradisional’, ritme kerja kami terasa begitu panjang. Kami harus memutar otak untuk memproduksi compact disc berisi karya lama LPMS Ideas yang digitalisasi, kaos, urunan, mengadakan kegiatan lain yang mampu menjaring dana, dan mencari iklan. Terkait pendanaan yang dihimpun untuk iklan, ada banyak sekali halangan yang kita buat sendiri. Misalnya tak boleh sponsor rokok, perusahan yang membantu memiskinkan negara, partai politik, dan sebagainya.
Hal tersebut sebenarnya bermula dari dana yang diberikan dekanat hanya 500 ribu rupiah. Tapi kami tak patah arang. Di balik itu semua, kami harus bekerja siang malam. Harus turun lapang berulangkali, memastikan fakta dan memastikan narasumber bisa diwawancarai. Menulis, lalu turun lapang lagi. Disiplin verifikasi. Editing berlapis siang malam.
Kertas-kertas berupa arsip, data, dan skrip wawancara berserakan bersama sisa kopi, laptop, alat tulis, dan isi asbak di dalam sekretariat. Berulangkali membersihkan ulang mental setelah bertemu narasumber yang bercerita sambil menangis, mengancam akan membunuh, dan yang berkelit susah ditemui.
Namun kami bangga menyepuh hari dengan estetika kebersamaan yang tak terhingga. Harus lalu lalang ke beberapa sekretariat Lembaga Pers Mahasiswa dan UKM untuk meminta kertas, meminjam komputer, meminjam scanner, tinta printer, dan sebagainya. Hari-hari kami jadi penuh kesadaran untuk terus berjejaring dan saling menguatkan. Beruntung akhirnya melalui percetakan berharga miring yang dikelola rekan pers mahasiswa di Jogja, kami mampu mencetak media itu.
Ketika kami mendistribusikan majalah tersebut ke rekan-rekan Pers Mahasiwa di Jogja, Malang, Surabaya, dan Bali. Rekan Persma di beberapa daerah tersebut mengira kami tengah berbohong. Mana mungunkin dari kampus hanya turun 500 ribu rupiah dipotong pajak. Bagi rekan pers mahasiswa yang lain dana segitu untuk buletin saja tak cukup, apalagi majalah.
Tak dinyana juga media itu yang pada akhirnya mampu menyabet juara pertama dalam dua kompetisi. Yang pertama kami memenangkan kategori kedalaman reportase saat mengikuti Ekspresi Award, April 2014. Sedangkan yang kedua kami mendapat juara pertama dalam Festival Media Aliansi Jurnalis Independen (AJI Indonesia), Mei 2014.
Tahun ini pula, tanpa sepeserpun dana dari kampus, kami mampu menggagas adanya media online berupa portal berita Ideas.id. Itu adalah portal berita pers mahasiswa pertama di Jember. Akan tetapi kami pun tidak pernah memprotes secara gamblang terkait, minimnya pasokan dana terhadap kerja-kerja internal redaksi maupun lembaga. Namun ketika menyampaikan berapa dana dari kampus yang kami dapat dalam pembukaan diskusi bedah konten majalah, seketika membuat kuping PD III memerah. Keesokan harinya beberapa dari kami disemprot dengan umpatan yang beraneka macam dari PD III.
Dosen yang mengerdilkan persoalan publik
Setelah memancing beberapa kalangan intelek untuk menarasikan gagasannya secara panjang. Saya berjanji pada diri sendiri akan berusaha berjarak dari facebook. Bagi saya ruang kecil tersebut berisi penuh cipratan permainan bahasa yang bersifat represif. Modus peredaman rasio tersebut diselipkan secara halus. Salah salu orang yang bergerak di dalamnya ialah Ilham Zoebazary.
Namun kolom yang dinarasikan oleh Ilham Zoebazary terebut, pada akhirnya membuat saya turut beropini terkait fenomena gugatan terhadap pers yang memakai tradisi bar-bar.
Saya tidak menulis seperti yang dikutip Ilham dengan meniadakan nama saya dalam kolom yang dia tulis, “Hari gini disuruh beretika?”. Akan tetapi yang saya tulis yaitu, “Cara berbicara pun ada tahapnya, jika cara berbicara khas elit birokra yang menye-menye dan sok ilmiah, rimba kutipan. Mana ada yang paham. Masih mending sih, daripada mata hati rabun dan tak menjaga nurani. Hari gini masih percaya etika ya?”
Kemudian saya juga menambahkan kalimat, “Sadam, kamu harusnya tahu diri lah, harus ber-etika… Lalu kalau kamu mengaku sebagai kaum intelektual, tak usah menyebarkan ancaman dengan tulisan pendek. Ya semacam Pak Ilham yang hanya mampu menulis satu paragraf dengan melampaui EYD. Tulis yang panjang, rasional, dan bertanggung jawab, lalu mari kita diskusikan.”
Silahkan dikutip berserta nama lengkap, akun saya bersifat personal. Saya pun siap bertanggung jawab atas apa yang saya publikasikan lewat akun tersebut. Saya yakin Ilham tahu mengenai hal itu.
Saya juga tidak menyalahkan Ilham ketika memelintir ucapan saya. Selama ini yang kebanyakan orang ketahui, dia merupakan tokoh lama yang menjadi panutan para pemuda pada setiap lapis jamannya. Peralihan dinamika ke-Indonesia-an juga bergantung dari argument orang semacam Ilham. Di balik tanggung jawab besarnya tersebut, mungkin dia hanya sedang lelah. Tentu karena berurusan dengan permasalahan yang lebih besar dari fenomena Fakultas Sastra. Dia juga menjadi bagian sebagai aparatus transformasi bagi kaum intelektual. Maka dari itu saya justru merasa sangat beruntung dia mampu hadir di tengah kita sembari berupaya menjernihkan suasana. Pak Ilham menjadi bagian dari kelas yang tidak sibuk dengan urusan emansipasi politik personal.
Terlepas dari Pak Ilham atau siapapun. Saya hanya menyayangkan jika para aparatus transformasi, entah itu Dosen, Dekan, Pembantu Dekan, atau apapun hanya disibukkan dengan dinamika kampus yang remeh. Mengapa orang yang mengaku pernah menjadi aktivis revolusioner, hanya mampu berdiam diri menyaksikan hasil riset yang menumpuk di meja. Bukankah penelitian tersebut memerlukan biaya yang sangat mahal. Tapi hasilnya sulit dijangkau oleh publik. Atau mungkin memang dibuat tak untuk dibaca. Sekedar memenuhi tuntutan penyandang dana untuk menyetor laporan penelitian saja.
Sedangkan terkait etika, merujuk pada kolom yang dibuat Pak Ilham. Menurut saya etika merupakan hasil ciptaan manusia yang senantiasa mengalami perkembangan definisi dan batasan. Rumus etika terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Maka saya tidak menyalahkan jika ada seseorang yang menyatakan bahwa mengkritik adalah tindakan nir-etika.
Sebab di abad pertengahan silam, perspektif gila atau melanggar etika bagi gereja ialah, personal yang tidak memiliki loyalitas pada gereja. Namun pemaknaan akan sesuatu terus berubah, sesuai dengan perspektif dan kepentingan pemegang kuasa. Di era kekinian justru pelanggar etika adalah mereka yang mengkritik kebijakan kampus dengan data dan fakta. Tentu saja karena perilaku tersebut tidak sesuai dengan keinginan elit birokrat, bukan lagi gereja.
Lontaran Pesudo-ilmiah elit birokrat
Stigma negatif disebar tanpa alasan mendasar, misalnya Wisasongko yang menyatakan bahwa beberapa terbitan LPMS Ideas tidak berimbang. Akan tetapi dia tak mampu mengemukakan bagian mana yang tidak berimbang. Lantas apa bedanya klaim tersebut dengan penanaman mitos negatif. Gagasan seolah demokrasi yang menghadirkan diri dengan menggandeng stigma, tak ada bedanya dengan gerakan puritan keagamaan. Ia bisa dengan mudah mengkafirkan mereka yang berbeda pendapat dengannya. Meski tanpa alasan yang rasional.
Jika tidak mampu menjawab pertanyaan mahasiswa, dia akan membalasnya dengan hardikan. Entah itu menyebut kufur, hina, dan miskin. Dampak umpatan pseudo-ilmiah yang dilontarkan Wisasongko tersebut menjadikan mahasiwanya sakit dan lemah. Mereka akan secara praktis dan dangkal memahami Islam, pemikiran cenderung doktriner dan tidak rasional. Nalar diabaikan dan berpaling menggunakan kosakata dari agama islam sebagai tameng dan senjata. Dari sana kemajemukan bangsa akan sirna, dihimpit oleh kekuasaan yang menginginkan homogen. Secara personal Wisasongko berubah menjadi perumus kebenaran yang mutlak.
Melalui struktur sosial Wisasongko sebagai subjek yang sedang menanak mahasiswa yang dianggap sebagai objek. Hal tersebut yang pada akhirnya merontokkan pandangan bahwa kampus sebagai ruang dialektika bertukar gagasan. Selama ini yang ada ialah komunikasi satu arah. Ketika lawan bicara tidak dimaknai secara utuh, ibaratnya Wisasongko seperti tengah mereparasi robot, bukan manusia. Ancaman bagi keberlangsungan hidup rasio akan menggurita di sektor wadah intelektual bangsa ini.
Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu, Wisasongko menyepakati argumen dari PR III, bahwasanya kebijakan ‘Jam Malam’ merupakan wujud kasih sayangnya terhadap mahasiswa. Sejak saat itu pula kegiatan mahasiswa tak boleh ada di malam hari. Sedangkan kegiatan yang diadakan oleh Universitas Jember yang rata-rata mewah, akan dengan mudahnya lolos dari peraturan yang mereka buat sendiri.
Jika memang cinta dengan anaknya, maka tak sesederhana melontarkan nasehat yang ujung-ujungnya untuk merepresif potensi. Sebagaimana tentang cinta sederhana versi Sapardi Djoko Damono. Meskipun saya rasa Sapardi adalah pembohong besar. Karena kisah cinta yang dia padatkan dalam metafor puisi cenderung mengharukan, sangat tidak sederhana. Terdiri dari rentetan upaya total untuk mencintai.
Tentang kayu yang tak pernah berani mengungkapkan sesuatu pada api. Barangkali karena api sengaja dihadirkan beserta karakter antagonisnya. Akan tetapi bagi kayu, api adalah segalanya. Itu sebabnya dia rela hilang, dia berani mengorbankan dirinya sendiri. Apa jadinya jika kayu tidak berani berkorban? Saya rasa api akan mati. Tiada.
Namun kayu cerdik sekali. Seolah dia sangat yakin jika dirinya dan api suatu saat akan menyatu. Sapardi memang membuatnya semacam itu. Mereka menyatu menjadi abu. Apa yang sederhana? Itu pengorbanan yang melelahkan. Betapa gilanya kayu, dia ingin memiliki sesuatu dengan cara menghilangkan dirinya sendiri.
Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Tan Malaka, “Jika ingin memerdekakan suatu kaum, maka kau harus rela kehilangan kemerdekaanmu sendiri.” Dari Tan Malaka saya mulai memahami bagaimana mencintai dan bagaimana berkorban, keduanya menjadi bagian dari kemanusiaan yang sulit dibantah.
Kami menolak intervensi
Kembali mendekat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap UKM di kampus manapun mendapatkan hak untuk diberikan fasilitas pendanaan. Sedangkan kampus berkewajiban untuk menyediakan fasilitas tersebut. Semula memang pendanaan untuk aktivitas mahasiswa diambil dari pajak masyarakat yang dihimpun negara. Kemudian negara menyerahkan kepada kampus untuk dikelola dan didistribusikan. Lantas betapa konyolnya jika terjadi klaim bahwa uang negara tersebut ialah milik personal dari Pembantu Dekan III Fakultas Sastra Universitas Jember. Dalam salah satu rekaman yang dimiliki LPMS Ideas, Wisasongko mengatakan, “Kalian meminta dana ke saya.”
Perlu kita ketahui juga bahwasanya setiap UKM di kampus bergerak secara otonom. Dalam hal ini misalnya LPMS Ideas yang bergerak dibidang pendistribusian wacana dan informasi. Memang benar mereka mendapatkan dana dari negara, akan tetapi keputusan gerak kelembagaan disepakati oleh orang internal mereka sendiri. Bisa dikatakan tetap menjaga kultur independensi. Menolak diintervensi oleh pihak di luar mereka.
Tanpa sikap otonom, kaum intelektual hanya akan setia pada rumusan epigon dan membebek.
Dari sana saya bisa memahami bahwa sebernarnya Wisasongko tidak bersalah. Dalam hal ini yang menurut saya patut disalahkan adalah jiwa kehewanan dari Wisasongko. Meskipun ada sedikit celah yang menggenangi analogi tersebut, ialah dari Aristoteles sendi bahwa yang membedakan antara manusia dan hewan tak lain rasio. Jika jiwa kehewanan menyalak dalam diri seseorang maka rasio akan menguap seketika.
Solusi logis
Saya bukan perumus kebenaran yang paling gahar di negeri ini. Namun ijinkan saya sekedar mengingatkan kembali, terkait sebuah solusi bagi delik pers.
Inti dari mengapa Wisasongko melakukan pendisiplinan ulang terhadap kerja-kerja jurnalistik LPMS Ideas. Tentu agar memudahkan dirinya dalam melakukan kontrol dan pengendalian. Cara ungkapnya lewat penyebaran anggapan darinya, bahwasanya produk jurnalistik yang dikelola oleh LPMS Ideas dianggap tidak seimbang, atau dalam istilah jurnalistik cover both side.
Namun bagi saya letak ketidaksesuaian kedewasaan dalam berpikir dan bertanggung jawab Wisasongko ialah; Pertama barangkali dia tidak tahu secara langsung di mana letak ketidak berimbangan tersebut. Sedangkan yang kedua, pilihan mengungkapkan ketidakberimbangan lewat oral sekaligus dibumbui ancaman yang bersifat represif.
Intimidasi yang dilakukan Wisasongko terhadap salah satu reporter kami adalah batu kecil yang mengganjal. Sebab jurnalis maupun perusahaan pers yang mengalami ancam dan intimidasi, akan berpotensi kehilangan kebebebasan dalam menyampaikan informasi yang patut diketahui publik. Manakala pers tak lagi bebas, sesungguhnya elemen yang paling dirugikan adalah masyarakat itu sendiri.
Penaklukan dan pengendalian akan mengunci mati laju hidup hak asasi manusia. Maka dari itu setiap Pers Mahasiswa, khususnya LPMS Ideas mengupayakan keberadaan pers bebas dan bertanggung jawab. Bebas dari sensor, ancaman, pembredelan, intervensi.
Perilaku Wisasongko tersebut sangat beresiko. Dia berada dalam struktur yang lebih tinggi daripada mahasiswa maupun Unit Kegiatan Mahasiswa. Maka perilaku tersebut dapat disayangkan akan menjadi panutan bagi elemen di bawah, samping, atau atasnya. Jika Wisasongko tidak tahu secara langsung bagian mana yang tidak berimbang dalam pemberitaan produk LPMS Ideas, maka bisa dianggap sebagai imajinasi belaka.
Sebagai pekerja intelektual, bukankah Wisasongko dekat dengan kerja-kerja ilmiah yang mengharuskan dirinya bertanggung jawab atas hipotesisnya. Oleh karenanya harusnya Wisasongko secara disiplin mampu menerangkan raison d’etre dari hipotesis yang muncul dalam dirinya. Sedangkan terkait hipotesis ranum yang dia munculkan lewat verbal adalah bagian dari kelalaian pekerja intelektual. Dari sana bisa kita ketahui bahwasanya Wisasongko sedang menghembuskan kesaksian palsu ke tengah-tengah publik. Namun ketika dikonfirmasi, bagian mana yang tidak berimbang, dia hanya bisa balik mengancam.
Saya tak mau memandang tugas dan fungsi pers secara positivistik. Karya jurnalistik merupakan ilmu pengetahuan yang tidak tetap. Tidak bersifat mutlak. Dalam artian fakta dan beberapa hal yang terkandung di dalamnya bersifat senantiasa mengalir. Sederhananya tidak selalu benar atau segera bisa dijadikan kitab suci setelah dipublikasikan. Maka dari itu para pegiat jurnalistik memerlukan keberadaan pembaca aktif sebagai pemantau. Untuk mengatasi gagasan yang melampaui kode etik, maka publik diberi fasilitas berupa hak jawab.
Sederhananya ada dua hak bagi publik untuk menggugat kerja pers yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999. Pertama yaitu, menggunakan hak jawab. Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan, terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan yang kedua yaitu, penggunaan hak koreksi. Hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers. Baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
Maka dari itu, sudah sewajarnya Wisasongko atau pembaca yang lain menggunakan hak tersebut. Di sisi lain, sebenarnya kami sangat antusias dengan hadirnya respon dari publik. Bagi kami melakukan kerja-kerja jurnalistik merupakan sebuah upaya untuk menjemput kritik. Sederhananya jika ada yang mengkriti otomatis ada celah bagi karya kami. Untuk selanjutnya publik yang mengkritik akan secara bertanggungjawab menyampaikan data dan fakta bandingan. Dari sanalah kita bisa selangkah lebih maju dari fenomena yang ditangkap di awal. Kami juga tidak mau terjebak dalam represi kuasa.
Kami yakin bahwa mahasiswa manapun yang berpikir dan bertindak maju menolak teori agung dan aturan yang memusat. Apalagi peraturan atau pengendalian yang disertai dengan ancaman. Ada baiknya jika setiap kebijakan yang menyangkut hak dan kewajiban mahasiswa dirumuskan bersama. Sebab kebijakan di ruang manapun yang datang dari atas lalu ke bawah, cederung bersifat eksploitatif. Harusnya pola kebijakan ialah bottom-up, atau dengan kata lain dari bawah ke atas.
Dominasi bersifat represif yang selama ini ada, hadir bersama kolonialisasi kebijakan-kebijakan kampus ke dalam kehidupan mahasiswa. Untuk menjaga dari terserangnya penyakit, maka harusnya disediakan ruang yang bebas bagi terwujudnya komunikasi yang dialogis. Dari sanalah akan berkembang biak keragaman gagasan yang bersifat kolektif. Sedangkan ruang Ideas.id atau produk LPMS Ideas yang lain, hanya ruang publik sementara bagi setiap sivitas akademika. Ruang kritik yang semestinya, di saat kita berkumpul untuk berdialektika dan saling menguatkan di dunia nyata.[]